 Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,
uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi
ekonomi global di awal abad 21.
Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,
uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi
ekonomi global di awal abad 21.
(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)
Masa Gunting Sjafruddin
Saya pernah melihat suatu berita yang berisi foto seorang wanita di
Amerika Serikat yang sedang berdemostrasi memprotes kondisi ekonomi. Ia membawa
poster berbunyi:
“I don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”
Maafkan perkataan kasar dan tidak sopan di atas. Arti kata f#¢ks
sebenarnya adalah ..... (maaf kata ini sangat tidak sopan), tetapi secara
informal berarti agak lain. Kalimat di atas adalah sebuah lelucon satiris.
Tetapi nilai leluconnya hilang kalau diterjemahkan secara sopan. Namun demikian
saya akan coba untuk memberi terjemahannya yang agak sopan:
“Saya tidak bergairah lagi terhadap seks, karena
pemerintah sering memperkosa saya.”
Terjemahan ini rasanya kok masih kurang lucu. Terlepas dari lucu atau
tidaknya, kalimat di atas adalah kalimat yang tepat untuk diucapkan oleh orang
yang punya uang pada tahun 1950 dan dan mengetahui apa yang akan terjadi 40
tahun kemudian.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia bulan November 1949, De Javasche
Bank yang merupakan bank swasta yang sahamnya diperdagangkan di bursa
Amsterdam, masih berfungsi sebagai bank sentral di wilayah republik. Walaupun
demikian, nampaknya De Javasch Bank seperti singa ompong. Kekuasaan moneter dan
keuangan dipegang oleh menteri keuangan. Dan ini bisa dilihat dari beberapa
keputusan pemerintah.
Setelah pengakuan kedaulatan republik bulan Desember 1949, pemerintah
republik menyadari akan banyaknya uang yang beredar di negara yang masih baru
ini. Oleh sebab itu perlu diadakan pengurangan uang yang beredar. Pada bulan
Maret 1950 pemerintah melakukan suatu ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan
nama Gunting Sjafruddin. Yang dimaksud dengan Gunting Sjafruddin ialah
keputusan pemerintah untuk menggunting pecahan mata uang rupiah yang
dikeluarkan NICA (pemerintah pendudukan Belanda) dan De Javasche Bank di atas Rp
5 menjadi dua. Uang ORI tidak dikenakan ketidak-bijaksanaan pengguntingan ini.
Potongan sebelah kiri berlaku dengan nilai hanya setengahnya dan bagian
sebelah kanan tidak berlaku melainkan harus ditukarkan dengan obligasi berjatuh
tempo 40 tahun dengan bunga 3% per tahun.
Keputusan pemerintah inilah yang bisa membuat orang memaki: “I don’t
need sex anymore. Government f#¢ks me up.” Selama 40 tahun nilai riil rupiah terperosok ke dalam jurang, mungkin
jurang agak kurang tepat. Palung laut lebih tepatnya. Kalau tahun 1950 harga
emas resmi masih Rp 4,30 uang rupiah (uang masa itu) per gram. Pada bulan Maret
tahun 1990 harga emas (uang sejati) menjadi Rp 23.700 uang Orba atau Rp
237.000.000 uang Orla/ORI. Nilai yang tersisa hanyalah 0.0000018 % saja. Perhatikan,
ada 5 nol dibelakang desimal sebelum angka 18 yang ada artinya. Nilai ini
nyaris nol. Bond pemerintah, ketika jatuh tempo tahun 1990 nilainya kurang dari
toilet paper. Karena toilet paper masih bisa digunakan untuk menyeka
tinja. Sedang kertas sertifikat obligasi keluaran tahun 1950, kalau masih ada,
sudah terlalu tua untuk dipakai sebagai penyeka tinja. Saya tidak tahu apa yang
terjadi dengan obligasi pemerintah yang dikeluarkan semasa Gunting Sjafruddin
itu. Surat obligasi negara itu identik dengan surat sita dari negara, karena
uang yang dikembalikan dikemudian hari tidak punya nilai apa-apa.
Apa yang terjadi setelah gunting Sjafruddin sampai hancurnya nilai
obligasi yang juga merupakan bagian dari keputusan gunting Sjafrudin adalah
suatu kebetulan sejarah mengalir secara alami atau sebuah rencana jahat yang
disiapkan bersama gunting Sjafrudin. Pemerintah republik membeli De Javasche
Bank melalui bursa saham Belanda dengan harganya 8,95 juta Gulden atau Rp 3,22
milyar (ORI)[1]. De Javasche Bank kemudian dinasionalisasikan
dan dijadikan bank sentral Indonesia milik pemerintah. Dengan demikian bank
sentral di Indonesia bukan lagi bank swasta, melainkan bank pemerintah.
Semuanya berlangsung secara resmi, dengan menggunakan undang-undang, yaitu
Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tertanggal 6 Desember 1951.
Apakah langkah ini baik atau buruk, tergantung siapa yang mengatakannya.
Bagi orang komunis dan sosialis, langkah ini merupakan langkah yang bagus.
Tetapi bagi orang yang suka menabung, yang punya tabungan obligasi gunting
Sjafruddin, orang yang suka akan kemerdekaan berusaha, maka monopoli pencetakan
dan peredaran uang oleh pemerintah menjadi mimpi buruk. Bank Indonesia adalah
mesin cetak uang yang effektif. Dalam kurun 30 tahun saja sudah mencetak Rp 64,74
quadrilliun (ORI) atau Rp 64.740.000 milyar (ORI) atau 20.105.590 kali harga
yang dibayarkan ke Belanda. Bagi pembaca yang awam, arti quadrilliun adalah 1015
atau 1.000.000 milyar atau 1.000 triliun. Disitulah hancurnya nilai
obligasi yang merupakan bagian dari ketidak-bijaksanaan gunting Sjafruddin. “I
don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”
Saya tidak pernah membaca suatu buku yang membahas keputusan pemerintah
ini dengan fokus mengenai skala dan ukuran kejahatannya. Skalanya adalah
nasional dari Sabang sampai Merauke, ......eeh maaf salah, sampai Ambon saja,
karena pada waktu itu Merauke belum masuk wilayah Indonesia. Dan saya juga
tidak mau terlalu detail mengenai batas negara pada waktu itu. Kota Bula (Seram
Timur) bisa saja dijadikan kota batas wilayah timur, tetapi siapa yang tahu
Bula. Saya juga awalnya tidak tahu.Baru tahu ketika menulis dongeng ini.
Pemerintah berhasil menjaring sekitar 1,6 milyar rupiah dari 4,3 milyar uang kartal yang beredar.[2]
Atau sekitar 37,20% nya. Nilai Rp 1,6 milyar saat itu setara dengan 373 ton
emas. Skalanya besar sekali. Saya tidak yakin bahwa penjajah Belanda pernah
melakukan penyitaan uang dari Sabang sampai Ambon sebesar 373 ton emas. Buku
sejarah tidak pernah mencatat hal ini sebagai kekejaman pemerintah republik
kepada rakyatnya, seperti halnya Tanam Paksa yang sebenarnya berskala jauh
lebih kecil kekejaman pemerintah republik atau Negara Kesatuan RI.
Pada waktu pengumuman ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan nama Gunting
Sjafruddin, keadaan jadi heboh. Pengumuman sanering (pengguntingan uang) ini
dilakukan melalui radio dan pada saat itu tidak banyak yang memiliki radio.
Sehingga mereka yang tahu kemudian berbondong-bondong memborong barang. Yang
kasihan adalah para pedagang, karena barang dagangannya habis, tetapi ketika
mereka hendak melakukan kulakan uang yang diperolehnya sudah turun harganya.
Modalnya susut banyak. Tetapi, bukan hanya pedagang yang rugi, tetapi semua
orang yang memiliki uang keluaran Belanda. Nilai uang susut paling tidak 50%
dalam sekejap saja.
Pada tahun-tahun sekitar 1950an, pemerintah menerapkan sistem kurs ganda
terhadap mata uang US dollar. Ketidak-bijaksanaan ini juga dimulai seminggu
setelah Gunting Sjafruddin. Pada ketidak-bijaksanaan kurs ganda ini ada kurs
resmi yaitu Rp3,80 per US dollar ada harga kurs effektif untuk eksportir yaitu
Rp 7,60 dan ada harga kurs effektif untuk importir yaitu Rp11,40 per
dollar.
Pada dasarnya bagi importir yang memerlukan mata uang asing dan harus
membeli dollar akan dikenakan kurs effektif Rp11,40 per US dollar. Bagi
ekspotir yang memperoleh mata uang asing dikenakan kurs effektif Rp7,60 ketika
menukarkannya dengan rupiah. Dari perbedaan kurs effektif ini, pemerintah
memperoleh keuntungan untuk menutup defisit anggaran negara. Tentu saja tidak
semudah itu. Eksportir bak dikenai pajak eksport sebesar 66.70%. Siapa sih yang
suka dikenai pajak. Kalau ada celah, kenapa tidak menghindar? Eksportir (juga
berlaku bagi semua yang berpenghasilan dollar) akan cenderung menghindari dari
pada menjual dollarnya secara resmi. Oleh sebab itu perlu peraturan pemaksan,
harus ada instrumen pemaksa bagi pelaku
bisnis untuk tunduk dengan kemauan pemerintah. Aliran devisa dikontrol ketat
melalui BLLD (Biro Lalu Lintas Devisa). Penukaran resmi uang asing dapat
dilakukan di bank-bank devisa yang memperoleh ijin dari Lembaga Alat-Alat Pembayaran
Luar Negri (LAAPLN). Disinilah pasar resmi mata uang asing.
Apapun namanya, pajak, cukai, kurs ganda, kalau sudah 66.70%, walaupun
untuk pemerintah, banyak orang tidak rela. Angka 66,70% itu lebih kejam dari
beban taman paksa yang hanya 20%. Memang bentuknya berupa pengotrolan devisa
bukan seperti pajak, yang secara terang-terangan ditarik ke wajib pajak.
Pengontrolan dan pengkebirian mekanisme pasar yang berlebihan seperti ini
menyebabkan distorsi pasar yang besar. Orang akan selalu mencari jalan keluar.
Muncullah kurs saingan sehingga kurs dollar ada dua, yaitu kurs resmi dan kurs
Pasar Baru. Kurs resmi adalah kurs yang didasari oleh paksaan (coercion)
dan kurs Pasar Baru (atau pasar gelap lainnya) adalah kurs yang adil yang
muncul dari pasar bebas. Pasar gelap tempat pertukaran mata uang asing
berlangsung terus sampai tahun 1967, dimana pengontrolan devisa melonggar.
Saya sebut kurs yang tidak resmi ini sebagai kurs Pasar Baru karena kalau
pada masa itu anda jalan-jalan ke Pasar Baru Jakarta, sering ada orang mendekat
dan berkata pelan-pelan: “dollar pak...., dollar ibu”. Mereka mengajak
bertransaksi dollar. Kadang pasar uang di Pasar Baru di masa itu disebut pasar gelap. Kata pasar gelap ini
digunakan pemerintah pada hakekatnya untuk memberikan konotasi buruk. Padahal
sebenarnya adalah pasar bebas dan dilakukan diterang hari.
Ketidak-bijaksanaan kurs ganda ternyata membuat kekacauan dan umurnya
hanya kurang dari 2 tahun. Pada bulan Januari 1952, diberlakukan satu (1) kurs
resmi yaitu Rp 3,80 per US dollar. Ternyata itupun hanya berlaku sekitar 1
bulan. Karena pada bulan Februari 1952, rupiah didevaluasi menjadi Rp 11.40 per
dollar. Nilai rupiah menguap 67% hanya dengan sebuah peraturan. Beruntunglah
orang-orang yang menyimpan emas atau perak. Nilainya tidak tergerus oleh
peraturan pemerintah.
Selama tahun 1950 – 1953 pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk lumayan
karena adanya perang Korea yang membutuhkan minyak dan karet Indonesia. Ini
berlanjut terus sekalipun perang Korea telah usai. Pemulihan pasca Perang Dunia
II membantu menjaga permintaan barang dari Indonesia sehingga pertumbuhan
ekonomi juga masih lumayan. Dana investasi dari luar negri masuk, terutama dari
perusahaan-perusahaan Belanda yang semasa pendudukan Jepang dan revolusi nyaris
tidak ada kegiatan. Upaya menhidupkan kembali perusahaan-perusahaan Belanda ini
menjadi tersendat ketika api semangat nasionalisasi membesar. Dampaknya baru
terasa setelah tahun 60an, setelah usaha pengambil-alihan dan nasionalisasi
perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1960an.
Dalam dekade 1950, awalnya masyarakat merasakan kemakmuran. Barang
produksi dalam negri relatif murah. Ini dikarenakan oleh ketidak-bijakan
pemerintah mematok kurs rupiah terhadap dollar Amerika dibawah nilai riilnya.
Artinya bahwa konsumen disubsidi lewat subsidi rupiah oleh eksportir dan
produsen barang eksport atas paksaan pemerintah. Pada tingkat ini nilai rupiah
terlalu mahal. Secara teori, dollar ditukarkan dengan rupiah di tempat-tempat
resmi dimana peraturan pemerintah masih bisa dipaksakan dan selama kondisi ini
bisa dipertahankan. Keengganan untuk menukarkan dollar dan mata uang asing dan
cenderungan untuk membangkang timbul di kalangan eksportir dan sektor-sektor
ekonomi yang melakukan kontak dengan pasar internasional. Salah satu bentuknya
adalah penyelundupan karet. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyelundupan ini
cukup marak. Tetapi secara pasti sulit diketahui karena para penyelundup tidak
akan pernah mendatakan dirinya. Hanya dampaknya yang bisa dirasakan. Jurang
antara kurs resmi dan kurs Pasar Baru semakin melebar.
Bagi penjual karet, tindakan penyelundupan yang dilakukannya bukanlah hal
yang buruk. Dia hanya menjual secara langsung ke pembeli tanpa melalui jalur
pemerintah. Pada dasarnya keberadaan pemerintah tidak dibutuhkan. Penyelundupan
seperti ini selalu terjadi jika pemerintah tidak memberikan jasa (service) apa-apa, tetapi hendak memungut
uang. Pemerintah dianggap sebagai penganggu yang harus dihindari.
Reaksi pemerintah pusat kemudian adalah memperketat pengawasan dan
mengatasi laju pembangkangan ini pemerintah pada bulan Juni 1957 mengeluarkan
peraturan baru yaitu sistem Bukti Eksport atau BE (Keputusan Dewan Moneter
tanggal 18 Juni 1 957 No. 30).
Dengan peraturan ini eksportir tidak lagi memperoleh rupiah ketika
menukarkan uang asing (devisa) hasil eksportnya, melainkan Bukti Eksport (BE).
Nilai nominal yang dicantumkan pada BE mengikuti kurs Rp 11,40 per dollar. Akan
tetapi, eksportir bisa menjual BEnya di bursa BE dengan harga mengambang dan
pembelinya adalah importir atau perorangan yang mempunyai ijin resmi. Karena
nilai rupiah sangat overvalue (mahal)
dan BE adalah wujud lain dari mata uang asing, maka ketika dilepas ke pasar
yang mempunyai mekanisme pasar bebas, harganya melojak tajam untuk mengejar nilai
wajarnya. Belum ada setahun sistem BE diberlakukan, harga BE melonjak ke level
300% dari nilai nominalnya. Kemudian pemerintah melakukan campur-tangan lagi
dan membekukan harga BE pada level 332% dari nilai nominalnya pada bulan April
1958. Penghapusan BE baru dilakukan tahun 1959 setelah Dekrit 5 Juli 1959.
Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi semakin menebal di kalangan rakyat.
Orang mulai membandingkan jaman penjajahan Belanda (jaman Hindia Belanda)
dengan jaman kemerdekaan. Istilah jaman Normal bagi jaman Hindia Belanda
menjadi populer di saat itu. Dan jaman kemerdekaan bukan jaman yang normal.
Dari kaca mata para politikus, kondisi Indonesia setelah penerapan Gunting
Sjafruddin yang diwarnai oleh adanya penyelundupan dan ketidak-puasan terhadap
pungutan-pungutan dan pemaksaan-pemaksaan yang melebihi jaman sebelumnya (jaman
Hindia Belanda) bisa dianggap sebagai suatu peluang politik. Komoditi tetap
menjadi penggerak ekonomi pada pasca pengakuan kedaulatan. Jakarta sebagai
ibu-kota negara pada saat itu kurang bisa menjalankan fungsi sebagai pusat
perdagangan dengan segala fasilitas jasa keuangannya dan perdagangan. Artinya
perdagangan di daerah bisa berjalan tanpa Jakarta. Politikus yang berasal dari
daerah penghasil devisa menunjukkan dukungannya terhadap gerakan makar ekonomi
daerah. Barangkali mereka pikir: “Kenapa
harus menyerahkan hasil eksport daerahnya ke pemerintah pusat? Kenapa tidak
dimakan sendiri? Kalau demikian, saya akan kebagian” Mungkin itulah latar
belakang pendirian PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan
Permesta (1958 - 1961). Latar belakang pemikiran orang, tidak ada yang tahu
kecuali dirinya sendiri. Dan anehnya sekumpulan orang bisa melakukan hal yang
searah secara kolektif.
PRRI walaupun didukung dengan keuangan yang kuat untuk membeli senjata
yang lebih modern dari TNI, ternyata tidak mempunyai tentara yang handal,
sehingga mudah dikalahkan oleh pemerintah pusat. Dalam sekali serangan, PRRI
dan Permesta sudah bercerai berai, sebagian pemimpinnya lari keluar negri,
tertangkap atau terbunuh. PRRI secara resmi baru menyerah tahun 1961.
Jaman uang Gunting Sjafruddin berakhir dengan Dekrit 5 Juli 1959. Anggap
saja begitu. Tonggak sejarah dibuat oleh penulisnya. Dan untuk buku ini,
penulis menyukai Dekrit 5 Juli sebagai sebuah tonggak sejarah, karena episode
berikutnya semua hal yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran semakin
suram. GDP malah merosot, turun, pertumbuhannya negatif, mengkerut,
berkontraksi.
Pada periode rupiah Gunting Sjafruddin, banyak yang telah dilakukan
pemerintah terhadap rupiah dan tabungan rakyat Indonesia. Pertama penyitaan
tabungan rakyat Indonesia setara 373 ton emas. Memang tidak disebutkan sebagai
penyitaan melainkan ditukar dengan surat obligasi 40 tahun. Tetapi ketika
hutang itu jatuh tempo dan hendak dicairkan, nilai riil uangnya sudah nyaris
nol. Jadi sama saja dengan penyitaan.
Kedua, rupiah juga mengalami penyusutan nilai riil akibat tindakan
pencetakan uang bernafsu. Dalam masa 14 tahun sejak Bung Hatta mengumumkan
penggunaan mata uang republik yang bernama rupiah, nilainya telah terpangkas
84,5% dan hanya tersisa 15,5%. Itu menurut ukuran resmi. Kalau menurut tolok
ukur Pasar Baru (pasar gelap) yang tersisa hanya 1,89%, artinya sudah 98,11%
terpangkas. Sebulan setelah Dekrit 5 Juli 1959, Sukarno memperkecil jurang
antara nilai rupiah resmi ini dengan nilai kurs Pasar Baru yang pada waktu itu
mencapai hampir Rp 94 per dollar. Apa yang dikatakan pahlawan Bung Hatta 14
tahun sebelumnya di RRI mengenai rupiah, hanya tipu semata.
Dan dalam 10 tahun sejak Bank Indonesia (BI) didirikan, BI telah sukses
memangkas nilai riil rupiah 66,67% dan tersisa 33,33%. Itu penilaian
berdasarkan angka-angka resmi. Kalau berdasarnya pasar bebas, maka yang
terpangkas adalah 95,94% dan sisanya hanya 4,06% saja. Prestasi yang bagus
untuk BI yang baru berumur kurang dari satu dekade.
Rupiah menjadi mata-uang yang dihinakan di negaranya sendiri. Di
pasar-pasar gelap orang mau menukarkan rupiah dengan dollar di harga yang lebih
rendah dari pada harga resmi. Rupiah dinilai rakyat 2-3 kali lebih murah.
Rupiah adalah mata uang murahan. Di beberapa daerah orang lebih suka melakukan
barter. Jangan katakan bahwa rakyat sudah kehilangan rasa nasionalismenya.
Kalau sudah menyangkut hasil keringat, siapa perduli dengan nasionalisme.
[1] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d.
Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Pra Bank
Indonesia,
http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/Sejarah+Pra-BI/prasejarahbi_7.htm
[2] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d.
Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia,
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0D07105F-9EB6-4990-9C00-95C737F53EE2/800/PeriodePengakuanKedaulatanRIsdNasionalisasiDJB.pdf
Disclaimer:
Dongeng
ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada
cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam
periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi
adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.
![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)



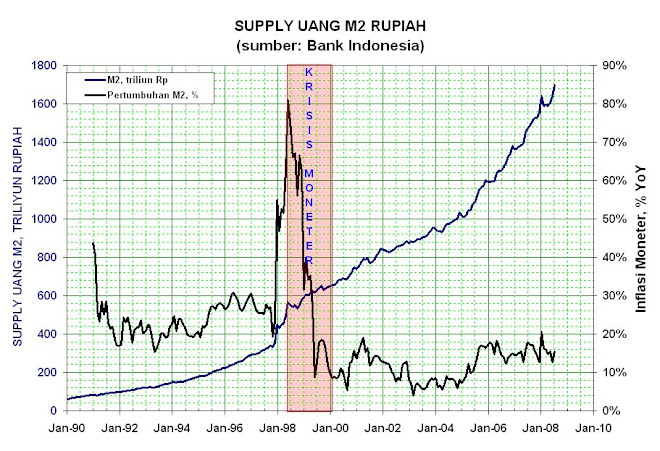
3 comments:
Pelajaran sejarah ekonomi dari Bung Imam yang sangat inspiratif
Sangat inspiratif Bung IS, sejarah memang tergantung dari sudut pandang yang menulis
Lanjutkan
Sejarawan yang baik adalah jika ia menyajikan data saja bukan analisa.
Kami di EOWI berusaha menyajikan data yang berupa tindakan pelaku sejarah dirangkai dengan implikasinya/akibatnya. Kemudian mempertanyakannya.
Ini adalah methodologi sain yang standard.
Post a Comment