 Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,
uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi
ekonomi global di awal abad 21
Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,
uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi
ekonomi global di awal abad 21
(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)
Periode Jaman Normal
Nama resminya yang
diberikan oleh para penulis buku sejarah adalah jaman “Penjajahan Belanda”. Periode sebelum tahun 1930an disebut jaman Normal oleh kakek-nenek yang pada saat penulisan buku
ini, mereka sudah berumur di atas 90 tahun, kalau masih hidup. Pemberian resmi
jaman Penjajahan bisa dimengerti karena para penulis buku sejarah yang direstui
oleh pemerintah harus memberi nama yang berkonotasi negatif terhadap jaman
Normal, untuk mendiskreditkan pemerintahan yang lalu (Hindia Belanda). Dan
Belanda yang tidak ikut menyusun buku sejarah Indonesia, tidak bisa membela
diri. Seperti halnya dengan kata Orde Lama (Orla, 1959 - 1966), penamaan ini
bisa bernada negatif karena nama itu adalah nama pemberian pemerintahan
berikutnya, yaitu Orde Baru (Orba, 1967 - 1997) dan pada saat penulisan sejarah
itu politikus Orla sudah disingkirkan habis-habisan pada saat pergantian rejim.
Berbeda halnya dengan jaman Reformasi, walaupun ada pergantian rejim, nama Orba
masih dipakai karena masih banyak anasir-anasir Orba yang bercokol di dalam
rejim Reformasi (1998 - ). Jadi..., sulit nama Orba ditukar menjadi Orde Lepas
Landas Nyungsep, atau nama yang
konotasi negatif lainnya. Catatan: nama Orde Lepas
Landas Nyungsep cocok untuk pemerintahan rejim Suharto karena di dekade akhir pemerintahannya dicanangkan sebagai era lepas lamdas (apapun artinya) dan kemudian kenyataannya diakhiri dengan ekonomi yang nyungsep.
Jaman penjajahan Belanda walaupun
nama resminya berkonotasi negatif, kakek nenek kita menyebutnya dengan nama
yang megah yaitu jaman Normal. Seakan-akan jaman Revolusi (1945 – 1950), jaman
Sukarno atau jaman Orba, tidak bisa dikategorikan sebagai jaman yang normal.
Kenyataannya memang demikian. Ciri jaman Normal menurut mereka ialah harga
barang tidak beranjak kemana-mana alias tetap. Di dalam keluarga, hanya suami
saja yang kerja dan bisa menghidupi anak sampai 12 dan istri (kadang lebih dari
satu). Ibu tetap di rumah merawat anak (yang banyak itu). Cukup sandang dan
pangan. Gaji 1 bulan bisa dipakai foya-foya 40 hari (artinya tanpa harus
menghemat, mereka masih bisa menabung). Dibandingkan dengan kondisi sekarang
(apakah anda di jaman reformasi atau di jaman Orde Baru), suami dan istri
bekerja untuk membiayai rumah dengan anak 2 orang dan itupun masih mengeluhkan
gaji yang pas-pasan.
Karena merasa masih penasaran dengan tingkat kemakmuran masa itu, saya
pernah tanyakan kepada mertua, berapa harga rumah dan makan dengan lauk yang
wajar. Harga rumah di Kali Urang 1000 Gulden. Makan nasi dengan lauk, sayur dan
minum 1 sen. Dengan kata lain harga rumah dulu adalah setara dengan 100.000
porsi nasi rames. Kalau tahun 2007 di Jakarta harga nasi rames Rp 10.000 dan
dianggap bahwa harga rumah yang bagus di Kali Urang setara dengan 100.000 porsi
nasi rames, maka harga tahun 2007 adalah Rp 1 milyar. Kira-kira itulah harga
rumah yang bagus di daerah itu. Jadi kalau rata-rata 1 keluarga terdiri dari 2
orang tua dan 10 orang anak dan bisa makan foya-foya selama 40 hari, pasti
penghasilannya setara Rp 9,60 juta lebih uang 2007 (setara 960 porsi nasi
rames). Ayah dari mertua saya adalah guru bantu. Gajinya 40 gulden per bulan
atau setara dengan 4.000 porsi nasi rames. Jumlah ini mempunyai daya beli
setara dengan Rp 40 juta per bulan uang 2007 (di Jakarta, harga nasi rames Rp
10.000 per porsi di tahun 2007 dan naik menjadi antara Rp 15.000 - Rp 20.000 di
tahun 2010). Dengan penghasilan seperti itu, di jaman Normal, seorang istri
tidak perlu kerja.
Gaji pembantu waktu itu 75 sen
per bulan atau setara dengan 75 porsi nasi rames. Berarti berdaya beli setara
dengan Rp 750 ribu uang tahun 2007. Atau Rp 1,25 juta uang tahun 2010. Padahal
gaji rata-rata pembantu rumah tangga di Jakarta tahun 2010 adalah Rp 600.000
per bulan. Jadi dibandingkan dengan jaman Normal, maka jaman Reformasi
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke II, pembantu rumah tangga
mengalami penurunan kemakmuran sebesar 50%.
Kita bisa telusuri terus gaji-gaji berbagai profesi pada masa itu seperti
dokter dan insinyur. Kesimpulannya bahwa daya beli waktu itu tinggi. Jadi tidak
heran kalau jaman penjajahan dulu disebut jaman Normal (artinya jaman lainnya
tidak normal).
Bagaimana bisa makmur? Jawabnya
mungkin sederhana sekali. Kemungkinan ada tiga hal yang membuat daerah Hindia
Belanda makmur dimasa itu. Pemerintahan Hindia Belanda tidak menggunakan uang
fiat melainkan uang sejati yang didukung oleh logam mulia dan tidak bisa
dicetak seenaknya. Yang kedua karena adanya Tanam Paksa (cultuurstelsel) yang kemudian diliberalisasi. Tanam Paksa
mengarahkan petani menanam komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi, bukan asal tanaman saja. Liberalisasi memungkinkan masuknya swasta yang
lebih mempunyai orientasi bisnis sehingga ekonomi menjadi lebih effisien. Dan
yang ketiga adalah pemerintahan yang kecil sehingga tidak memerlukan biaya yang
membebani pelaku ekonomi.
Dalam sistem moneter, penguasa keuangan dimasa itu adalah De Javasche Bank.
Bank sentral Hindia Belanda ini adalah bank swasta yang baru berdiri tahun 1828
dan diberi hak monopoli mengeluarkan uang. Dan uang yang dikeluarkan adalah
uang emas dan perak atau uang kertas yang bisa ditukarkan dengan logam mulia.
Dengan kata lain, uang kertasnya didukung oleh logam mulia, asset riil. Dengan
sistem uang sejati – uang yang emas dan perak atau yang didukung oleh cadangan
logam mulia, inflasi selalu terkendali. Pemerintah tidak bisa seenaknya
mencetak uang. Kestabilan harga bisa dijamin. Hanya mekanisme pasar antara
permintaan dan penawaran saja yang bisa mengendalikan harga, bukan faktor
moneter (pertambahan uang yang beredar). Baik itu harga bahan makanan, barang
konsumsi sampai pada harga jasa dan upah kerja. Memang selama periode ini terkadang
ada ganguan pada pasokan logam mulia semasa Perang Dunia I. Selebihnya semuanya
berjalan normal.
Mengenai Cultuurstelsel sebenarnya bukan hal yang baru pada saat itu, karena
Cultuurstelsel merupakan perluasan dari Preangerstelsel (Sistem Priangan) di
Jawa Barat yang diberlakukan sejak tahun 1677 atau 1,7 abad sebelum Tanam Paksa.
Tanah Priangan di serahkan Amangkurat II dari Mataram kepada VOC pada saat
Amangkurat II membuat persekutuan dengan VOC untuk menghadapi pemberontakan
Trunojoyo.
Tentang Tanam Paksa, banyak sejarawan Indonesia mengecam sistem ini.
Katanya kejam. Dan opini ini didukung oleh beberapa kalangan Belanda sendiri,
seperti Eduard Douwes Dekker asisten residen Lebak, Banten yang kemudian
menjadi seorang sastrawan penulis dengan nama samaran Multatuli. Bukunya yang
terkenal berjudul Max Havelaar (1860), berupa novel satiris yang berisi kritik
atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi dalam kaitannya
dengan Tanam Paksa. Novel adalah novel yang fiksi. Baik sebagian atau
seluruhnya. Walaupun tidak menutup peluang adanya novel yang didasari pada
kejadian nyata dan diungkapkan dengan bahasa yang hiperbolik. Apapun hakekat
yang sebenarnya dari Max Havelaar, novel ini bisa mempengaruhi sejarawan seakan
merupakan sesuatu yang pernah terjadi. Tanam Paksa itu buruk.
Bahasa Belanda Tanam Paksa adalah
cultuurstelsel atau dalam bahas
Inggrisnya cultivation system. Jadi
secara harfiah, cultuurstelsel
berarti sistem kebijakan pertanian. Pemberian nama Tanam Paksa adalah untuk
memberikan konotasi yang negatif terhadap kebijakan (atau ketidak-bijakan,
tergantung konotasi yang mau diberikan) yang diterapkan pemerintah Hindia
Belanda waktu itu. Kenyataannya adalah bahwa, pemerintah Hindia Belanda
mengharuskan petani penyewa tanah untuk menanami 20% dari tanahnya dengan
komoditi yang sedang laku di Eropa, yaitu kopi, gula dan nila dan hasilnya
diserahkan ke pemerintah sebagai uang sewa tanah dan penggunaan sistem
irigasinya. Tanah yang dikuasai Hindia Belanda tidak diperoleh secara gratis,
melainkan dengan biaya. Tanah konsesi Bagelen,
Banyumas, dan Kedu misalnya, diperoleh sebagai pembayaran bantuan
Belanda kepada Kraton Yogyakarta untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro dalam
Perang Jawa. Dalam perang ini 200 ribu orang di pihak Jawa mati dan 15 ribu
dari pihak Belanda mati serta menelan biaya 20 juta gulden dari pihak Belanda.
Sistem irigasipun diperluas untuk
memastikan bahwa semua sawah dan tanah pertanian yang dicetak (baru dan lama)
terpenuhi kebutuhan airnya. Masyarakat Jawa pada masa sebelum Tanam Paksa sudah
mengenal sistem irigasi yang sederhana, menggunakan bambu untuk mengalirkan air
sungai ke sawah-sawah. Pada masa Tanam Paksa ini Belanda membagun jaringan
irigasi primer dan sekunder. Sistem irigasi ini dilengkapi juga dengan tatakelola
airnya. Pemerintah Hindia Belanda mengetahui benar bahwa air sangat essensial
bagi perkebunan tebu, nila dan sawah. Tanpa pengairan yang baik, cultuurstelsel, tidak akan berhasil.
Dengan demikian, bisa dikatakan
angka 20%, dalam Tanam Paksa itu sebagai pajak penghasilan atau sewa tanah
dan/atau pembayaran atas layanan irigasi yang diberikan oleh pemerintah.
Saluran irigasi harus dirawat dan gaji para mantri (pegawai pengatur) air harus
dibayar. Tidak ada yang gratis.
Angka 20% ini kecil dibandingkan
pajak-pajak di jaman Republik Indonesia merdeka. Pajak penghasilan selama Orde
Baru dan periode sesudahnya mencapai 30% - 35%. Ini tidak termasuk pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak jalan, pajak barang mewah dan sederet
lagi. Dibandingkan dengan pajak penghasilan di masa Republik Indonesia merdeka
yang bisa mencapai 35% pada jaman Orba. Tanam paksa lebih baik dan penjajah
Belanda lebih bermurah hati dari pada politikus republik.
Kalau mau disebut konsesi
penggunaan tanah atau pajak, setoran Tanam Paksa yang 20% ini juga kecil
dibandingkan dengan porsi pemerintah republik dalam perjanjian kontrak produksi
sharing (kontrak PSC, Production Sharing
Company) dalam bidang eksplorasi dan
eksploitasi minyak semasa periode Orde Baru dan periode sesudahnya. Dalam
kontrak PSC, porsi pemerintah adalah 85% untuk produksi minyak dan 65% untuk
produksi gas. Padahal dibandingkan dengan Tanam Paksa resiko gagal dalam
eksplorasi jauh lebih besar dan itu ditanggung kontraktor penggarap. Menanam
kopi, tebu dan nila resiko gagalnya kecil. Siapapun yang mengatakan beban yang
harus dibayarkan kepada pemerintah (Hindia Belanda) sebesar 20% dari hasil
panen sebagai beban yang berat, mereka ini harus melihat kontrak PSC dan pajak
penghasilan di jaman Republik Indonesia semasa Orde Baru dan sesudahnya.
Pemerintah penjajahan Hindia
Belanda memang kejam, menariki 20% dari hasil pertanian. Dan pemerintah Republik
Indonesia lebih kejam lagi karena pajak yang ditariknya lebih tinggi. Itu
adalah sifat pemerintah, birokrat dan politikus. Yang ada adalah kejam dan
lebih kejam. Jadi kalau nenek-kakek kita dulu menyebut jaman Belanda ini
sebagai jaman Normal, maksudnya, jaman republik jauh lebih tidak enak. Yang
mereka tidak sadari ialah, bahwa kesengsaraan itu disebabkan oleh para
politikus penggerak roda pemerintahan.
Cultuurstelsel mengalami masa sosialisasi selama 10 tahun sejak tahun
1830, baru kemudian bisa secara effektif berjalan. Tetapi sepuluh tahun
kemudian, sekitar dekade 1850, sistem ini banyak dikritik karena terlalu banyak
campur tangan pemerintah. Muncul keinginan untuk meliberalisasi sistem
pertanian bahan-bahan komoditi. Liberalisasi baru dilakukan tahun 1870 dengan
diberlakukannya undang-undang agraria yang baru Agrarische Wet. Swasta diperbolehkan masuk di sektor bisnis
komoditi pertanian. Monopoli pemerintah dihapuskan dan peran swasta menjadi
dominan. Perkebunan-perkebunan baru dibuka. Tanaman-tanaman komoditi baru
diperkenalkan dan akhirnya perkebunan seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit,
nila, tebu dan tembakau bekembang. Perkebunan-perkebunan karet, teh, kelapa
sawit milik pemerintah sekarang banyak berasal dari perkebunan-perkebunan
Belanda di masa pasca Tanam Paksa.
Dengan beban pajak yang relatif
ringan, mudah diduga bahwa ekonomi menjadi marak yang memungkinan infrastruktur
bisa dibangun secara ekonomis. Sistem perkereta-apian dibangun dan mulai
dioperasikan tahun 1864. Karena latar belakang pembangunan jaringan kereta api
ini adalah kebutuhan ekonomi bukan karena kepentingan politik, maka peran
swasta menjadi dominan. Mengikuti permintaan pasar, jaringan kereta api terus
berkembang melewati masa boom ekonomi
1920an dan depresi 1930an. Dan hingga tahun 1939, panjang rel telah mencapai
6.811 km.[1]
Dilihat dari segi
pemerintahannya, menurut penuturan orang-orang tua dulu, bahwa pada jaman
Normal ini hanya ada 5 kementerian saja, yaitu:
- Departement van Economische Zaken (Ekonomi)
- Departement van Sociale Zaken (Sosial)
- Departement van Verkeer en Waterstaat (Perkerjaan Umum)
- Departement van Binnenlandsche Zaken (Dalam Negri)
- Departement van Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Budaya/Kepercayaan)
Tidak ada departemen Penerangan
dan Informasi, tidak ada departemen Pertanian, Kehutanan, Perkebunan. Tidak ada
kementerian urusan ibukota Jakarta, tidak ada departemen Pariwisata, Olah Raga
dan Pemuda, dan departemen-departemen lain. Kecilnya birokrasi tidak hanya
membuat budget pemerintah untuk membayar gaji pegawai dan menyediakan kantornya
rendah, tetapi juga membuat rantai perijinan birokrasi menjadi pendek. Parlemennya
juga kecil. Anggota Volksraad (Dewan Rakyat, parlemen) hanya 38 orang.
Dibandingkan dengan anggota DPR – Dewan Perwakilan Rakyat (2009) adalah 560
orang ditambah dengan DPD – Dewan Perwakilan Daerah 132 orang. Dan kalau mau
dihitung dengan DPR-D tingkat I dan II, total menjadi 15.987 orang. Tentu saja
pembandingan ini tidak aci, karena
dewan kota di jaman penjajahan Belanda juga harus dimasukkan. Sebagai
perbandingan yang adil – jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1920 ke 2009 naik
4,2 kali lipat yaitu dari 54 juta jiwa (tahun 1920) menjadi 226 juta (tahun 2009).
Sedangkan anggota parlemennya naik 18,2 kali lipat. Kementeriannya naik 7,5
kali lipat. Jangan heran kalau pajak penghasilannya naik 12 kali lipat.
Ekspansi birokrasi pemerintahan republik lebih cepat daripada kenaikan
populasi, oleh sebab itu beban oleh republik (jauh) lebih berat dari pada beban
yang diberikan pemerintahan penjajahan Belanda (di jaman Normal) kepada rakyat.
Pajak upah (penghasilan) di jaman Normal 3%.
Negara sekecil Belanda tidak
mungkin menjajah dengan birokrasi besar. Kalau dibandingkan dengan pegawai
negri republik tahun 2009 misalnya, untuk menjalankan republik Indonesia
diperlukan 4,4 juta pegawai negri. Ini tidak termasuk calon pegawai negri yang
biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk menunggu sampai pengangkatan,
serta pegawai tidak tetap yang tidak pernah bisa jadi pegawai negri. Dan pada
saat yang sama (tahun 2009) populasi Belanda hanya 16,6 juta orang dengan jumlah
laki-laki dewasa (25 – 60 tahun) sebanyak 4,2 juta. Kalau pada tahun 2009 harus
memerintah Indonesia dan semua aparat birokrasinya dari Belanda, maka semua penduduk
laki-laki Belanda dewasa (25 – 60 tahun) harus menjadi pegawai urusan negri
jajahan. Ini dengan catatan bahwa pribumi tidak ada yang mau jadi antek-antek
penjajah. Pengandaian ini mungkin terlalu berlebihan. Baiklah..., kalau hanya separo
saja pegawai negri yang Belanda dan sisanya orang lokal, maka 50% dari
laki-laki dewasa Belanda harus menjadi pegawai urusan negri jajahan. Ini masih
terlalu bayak.
Kalau perandai-andaian ini
ditarik ke jaman Normal dulu, maka
kesimpulannya akan sama, yaitu bahwa penduduk Belanda tidak akan bisa
mengisi posisi birokrasi ala republik Indonesia yang seperti ini.
Periode ini, di Jawa diluar
wilayah kesultanan Jawa, melahirkan pedagang-pedagang yang tangguh seperti Oei
Tiong Ham raja gula Asia, Tasripin pengusaha dari Semarang, Nitisemito raja
kretek dari Kudus. Usaha Oei Tiong Ham yang ada di Indonesia masih tersisa
sampai setelah kemerdekaan dan dinasionalisasi ketika jaman Sukarno. Nitisemito
yang agak eksentrik konon ceritanya menempeli dinding rumahnya dengan uang
gulden perak. Masih banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses dari Jawa yang
kurang terkenal dan juga dari Sumatera seperti Sutan Lerang eksportir
produk-produk lokal ke Singapura memiliki tanah sepertiga sampai setengah kota
Padang, ahli warisnya (generasi ke 4) sampai sekarang masih bisa menjuali tanah
warisannya secara bertahap.
Yang disebutkan di atas tidak
termasuk raja-raja yang juga mempunyai industri. Seperti kraton Mangkunegara
dengan pabrik gula Colo Madu dan Tasik Madu serta kraton Yogya dengan pabrik
gula Grisikan nya.
Oleh kakek-nenek kita yang
mengalami hidup dimasa ini, periode ini disebut jaman Normal mungkin karena
pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia dan
pemerintah pusatnya yaitu Belanda. Pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda mulai
mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia dan penjajahnya sekitar tahun 1880an.
Sebelumnya selalu lebih lambat (Grafik VII - 2). Hal ini berakhir
sampai masuknya Jepang ke Hindia Belanda tahun 1942. Ekonomi republik
eks-Hindia Belanda terpuruk dan tumbuh kerdil dibandingkan pertumbuhan ekonomi
dunia dan ekonomi mantan-penjajahnya.
Grafik VII - 2 Perbandingan
pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda, Dunia dan Belanda dari tahun 1810 sampai 1970.
GDP per kapita dalam (1990 $).
Kombinasi pajak yang relatif
rendah pada periode jaman Normal ini, kebebasan pasar dan kebebasan berusaha
serta penggunaan uang sejati (emas dan perak) yang membuat inflasi (pencetakan
uang) yang terkendali, membuat ekonomi Hindia Belanda bisa tumbuh sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Layaklah sekiranya kakek-nenek kita menyebut masa
ini sebagai jaman Normal. Walaupun mereka tidak tahu mengenai ekonomi, tetapi
mereka bisa merasakannya. Nenek saya yang hanya bisa baca-tulis dalam
Arab-Melayu (Arab gundul) dan membaca huruf latin, berprofesi sebagai penyewa
tanah pemerintah, yang dikelolanya sebagai sawah padi. Sedang kakek saya
bekerja sebagai guru. Dari profesinya, mereka bisa memiliki dua buah rumah di
Semarang dan tabungan yang cukup. Sayangnya tabungannya habis dicuri maling
ketika masa revolusi kemerdekaan.
Sebagai pembanding antara jaman Normal dan jaman Indonesia merdeka,
anak-anak dari kakek-nenek saya rata-rata sarjana; ada yang dokter, sarjana
hukum, doktorandus, tidak ada seorangpun yang bisa memiliki rumah dua seperti
orang tua mereka yang pendidikannya rendah. Bahkan ada salah satu anaknya dari
12 anaknya yang tidak mampu membeli rumah. Rumah bisa diperolehnya karena
memperoleh uang pesangon penggusuran (uang pindah). Saya tidak tahu secara
pasti apakah kehidupan kakek dan nenek saya cermin masyarakan dimasa itu atau tidak.
Tetapi itulah hakekat arti Normal dan merdeka menurut kakek dan nenek saya.
Sebuah opini yang subjektif.
Jaman Normal tidak selamanya
makmur dan ekonomi bisa tumbuh berkesinambungan. Pada masa depressi dunia tahun
1930an, Hindia Belanda juga terkena imbasnya. Ekonomi mengalami kontraksi. Di
tengah berkecamuknya Perang Dunia II, kepercayaan rakyat, terutama kelas
menengah dan kelas atas, terhadap uang kertas gulden menyurut. Uang perak
secara perlahan hilang dari peredaran, masuk ke dalam celengan dan lemari besi
orang-orang berduit atau dipendam di dalam tanah. Ketika Jepang masuk, mereka
juga memintai uang-uang perak yang ada dan ditukar dengan rupiah pendudukan
Jepang yang terbuat dari kertas. Ada penduduk yang menyerahkannya dan banyak
yang tetap memendamnya di dalam tanah. Orang-orang yang memutuskan untuk
membangkang dan tetap memendam uang-uang peraknya di dalam tanah, terbukti
dikemudian hari sebagai orang yang beruntung. Kata beruntung tidaklah terlalu
tepat. Yang tepat adalah: “tidak dirugikan”. Uang perak dan emasnya tidak
beranak, tetapi juga tidak berkurang nilai riilnya.
[1] Proyek Efisiensi Perkeretaapian, Siti
Khoirun Nikmah & Valentina Sri Wijiyati, International NGO Forum on
Indonesian Development, Working Paper No.1, 2008
Dongeng
ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada
cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam
periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi
adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.
Ekonomi
(dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara
eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai
anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab
atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi
dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan
informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda
mentraktir EOWI makan-makan.

![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)



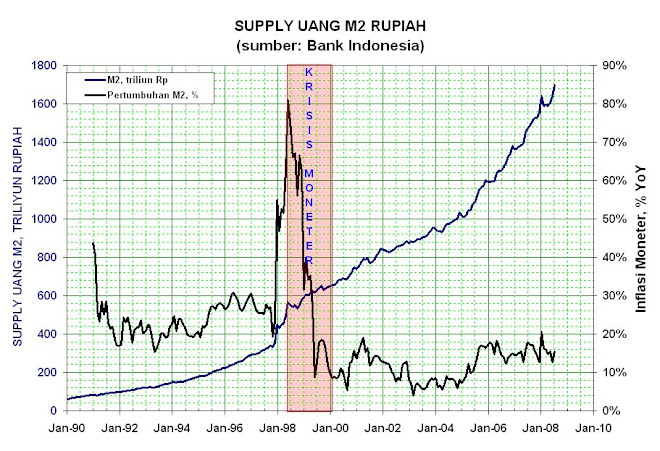
1 comment:
halo bro IS,
komentar nih - inflasi selain karena money printing juga disebabkan supply - demand yang tidak seimbang
jumlah manusia jaman dulu kan masih sedikit banget
Post a Comment