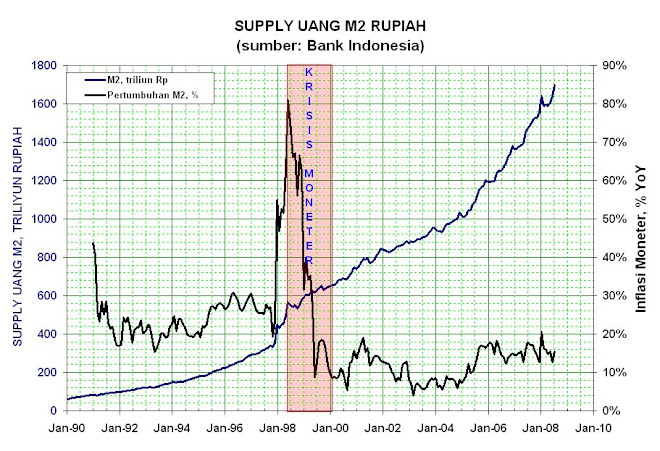Menuju Negara yang Makmur (Bagian II)
Pada bagian pertaman tulisan berseri ‘Menuju Negara yang Makmur’, kami di Ekonomi Orang Waras dan Investasi [EOWI] bertanya “Bagaimana?”, sebagaimana dengan sub-judul dari artikel itu [link]. Tulisan kali ini adalah bagian ke dua yang sebagian diambil dari situs Akal&Kehendak.
Ketika Barack Obama berpidato di acara $170 juta inaugurasi nya, kami pikir Barack akan membuat retorik semacam yang dibuat oleh pendahulunya, presiden dari partai Demokrat lalu John Kennedy. Retorik Kennedy yang terkenal adalah:
‘Don’t ask what the country can do for you, but ask what can you do for the country.’
Tentu saja kami tidak berharap Obama menyatakan yang sama, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dialami US sekarang, krisis liquiditas, depresi deflasi dan ambruknya sistem keuangan US. Harapan kami Obama akan mengatakan:
“Don’t ask what banks, the Fed, AIG, Merrill Lynch, Freddie and Fannie can do for you, but ask how much money you can give to them or my $170 million inauguration.”
Ini sejalan dengan makin banyaknya uang pembayar pajak yang dipakai untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini dan memberi kemewahan bagi CEO (Chief Executive Officer) mereka. Jangan protes, kira-kira begitulah maksud ucapan retorik itu.
Kalau melihat prilaku pemerintah, apakah anda tidak pernah bertanya, apakah kita masih perlu pemerintah?
APAKAH KITA PERLU PEMERINTAH?
Beberapa waktu lalu EOWI melakukan jajak mendapat mengenai perlu-tidaknya seorang gubernur untuk Jakarta. Majoritas responden menjawab ‘tidak perlu’ atau ‘boleh dicoba tidak usah ada gubernur Jakarta’. Ini sejalan dengan pilihan penduduk Jakarta. Fauzi Bowo yang katanya memenangi pemilihan gubernur Jakarta ternyata kalah dengan kursi kosong (tidak memilih). Ternyata kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di provinsi-provinsi lain. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil akhir sebagian pilkada di Indonesia tahun 2008. Yang menarik kursi kosong menang mutlak mayoritas (lebih dari 50%) di Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Mungkin masih banyak lagi daerah-daerah dimana kursi kosong menang mutlak tetapi tidak kami liput dan masih ada sengketa antar peserta mengenai hasilnya.

(klik tabel untuk memperbesar)Pada bagian pertaman tulisan berseri ‘Menuju Negara yang Makmur’, kami di Ekonomi Orang Waras dan Investasi [EOWI] bertanya “Bagaimana?”, sebagaimana dengan sub-judul dari artikel itu [link]. Tulisan kali ini adalah bagian ke dua yang sebagian diambil dari situs Akal&Kehendak.
Ketika Barack Obama berpidato di acara $170 juta inaugurasi nya, kami pikir Barack akan membuat retorik semacam yang dibuat oleh pendahulunya, presiden dari partai Demokrat lalu John Kennedy. Retorik Kennedy yang terkenal adalah:
‘Don’t ask what the country can do for you, but ask what can you do for the country.’
Tentu saja kami tidak berharap Obama menyatakan yang sama, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dialami US sekarang, krisis liquiditas, depresi deflasi dan ambruknya sistem keuangan US. Harapan kami Obama akan mengatakan:
“Don’t ask what banks, the Fed, AIG, Merrill Lynch, Freddie and Fannie can do for you, but ask how much money you can give to them or my $170 million inauguration.”
Ini sejalan dengan makin banyaknya uang pembayar pajak yang dipakai untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini dan memberi kemewahan bagi CEO (Chief Executive Officer) mereka. Jangan protes, kira-kira begitulah maksud ucapan retorik itu.
Kalau melihat prilaku pemerintah, apakah anda tidak pernah bertanya, apakah kita masih perlu pemerintah?
APAKAH KITA PERLU PEMERINTAH?
Beberapa waktu lalu EOWI melakukan jajak mendapat mengenai perlu-tidaknya seorang gubernur untuk Jakarta. Majoritas responden menjawab ‘tidak perlu’ atau ‘boleh dicoba tidak usah ada gubernur Jakarta’. Ini sejalan dengan pilihan penduduk Jakarta. Fauzi Bowo yang katanya memenangi pemilihan gubernur Jakarta ternyata kalah dengan kursi kosong (tidak memilih). Ternyata kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di provinsi-provinsi lain. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil akhir sebagian pilkada di Indonesia tahun 2008. Yang menarik kursi kosong menang mutlak mayoritas (lebih dari 50%) di Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Mungkin masih banyak lagi daerah-daerah dimana kursi kosong menang mutlak tetapi tidak kami liput dan masih ada sengketa antar peserta mengenai hasilnya.

Jelas, sebenarnya majoritas (mutlak, atau tidak mutlak) dari rakyat Indonesia tidak merasa perlu adanya pemerintah (daerah). Mungkin juga pemerintah pusat.
Sebelum kita memutuskan untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu pemerintah, ada baiknya kita lihat apa arti kata pemerintah. Berikut ini adalah tulisan dari situs sahabat. Tulisannya agak bersifat akademis. Maklum, pengelola situs ini mungkin berkecimpung dibidang akademis atau sejenisnya. Mungkin beliau ini punya gelar PhD, philosophical Doctor.Imam Semar juga punya gelar PhD tetapi artinya – Permanently Head Damage.
ASAL (KATA) PEMERINTAH
Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. I, Edisi 15, Tanggal 30 Desember 2007
Esei singkat di penghujung tahun 2007 ini mengangkat satu pertanyaan: Kapan, di mana dan bagaimana kata ’pemerintah’ muncul pertama kali?
Sejak bertemu Onghokham pertama kali di akhir musim dingin bertahun-tahun lalu hingga beliau wafat, jawaban pertanyaan tersebut masih menggantung; dan hal ini cukup mengecewakan.
(Sebagai sejarawan, Onghokham unik dalam hal ia memfokuskan pusat penelitiannya pada manusia. Setiap kali saya mendapati bukunya di perpustakaan atau di toko buku, sedapat mungkin saya sisihkan waktu untuk mencari jawabannya. Pada ‘ritual’ terakhir, saya cuma menemukan dalam Wahyu Yang Hilang, satu bab yang menarik tentang korupsi yang sejak dulu selalu mendampingi evolusi kekuasaan dan pemerintahan; juga bab tentang pergerakan modal di tangan para pengusaha Cina.)
Maka, maklum, tanpa hasil ‘penggalian’ sejarawan tersebut, artikel ini cuma dapat berhipotesis: bahwa kata ‘Pemerintah’ dipakai pertama kali di masa pra-Indonesia; dia muncul perdana di masa awal bangkitnya semangat kebangsaan, jauh sebelum revolusi fisik menjelang kemerdekaan.
Tentang kapan persisnya, di pamflet atau di koran mana, oleh siapa, dalam aksara apa—Arab gundulkah?—serta untuk mengacu ke pemerintahan yang mana, semuanya masih harus dicari melalui penelitian filologis, sosiologis, atau sejarah yang mendalam.
Sesuai definisinya, pemerintah berarti ’pemberi perintah, komando atau instruksi’. Nuansanya yang militeristik dan/atau paternalistik mencerminkan asimetri antara yang memerintah dan yang diperintah.
Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya. Terminologi ini tentunya cukup cocok untuk mengacu pada hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan subyek jajahannya. Atau hubungan antara orangtua dan anak—sebelum sang anak beranjak dewasa dan menjadi manusia otonom.
Apakah istilah tersebut pantas diterapkan oleh/pada individu-individu yang konon memiliki kesamaan derajat dan hak? Besar kemungkinan pembaca dapat setuju jawaban ini: tidak.
Jika demikian, apa tidak sebaiknya diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai? Bukankah pada dasarnya, negara adalah kita?
Yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan keberadaan pemerintah itu sendiri. Mempertanyakan muasal kata tersebut hanyalah awal bagi napak tilas yang krusial untuk menelaah secara kritis idiosinkrasi kita dalam memandang fenomena pemerintahan dan konsekuensinya bagi fenomena sehari-hari.
Sama halnya dengan konsep-konsep raya seperti negara, kebangsaan, nasionalisme atau lainnya, konsep pemerintah selalu penting dan relevan ditanyakan dan harus terus dipertanyakan oleh setiap generasi.
Satu klaim yang mendasari introspeksi ini adalah bahwa di dalam kata “pemerintah” terekam jejak yang relatif jelas bagi evolusi sebuah institusi negara, yang kita jadikan means untuk suatu end.
Indonesia modern sebagai sebuah tujuan memang digagas dan dibayangkan oleh segelintir intelektual (baca: politikus- EOWI). Ia diwujudkan bersama dalam berbagai cara, termasuk lewat jalur keras revolusi fisik. Satu hal dapat dipastikan: sebelum negara ini terbentuk, kita sudah ada. (Terlepas dari pandangan Nozick yang cukup menarik tentang negara yang minimalis, tesisnya tentang asal negara berdasarkan sebuah immaculate conception, sangat sulit diterima akal.)
Upaya menuju sebuah Indonesia bermula dari gagasan. Lebih tepatnya, ia lahir dari pertarungan berbagai gagasan yang acapkali berlawanan, meski seringkali tampak saling komplementer.
Lebih lanjut, pemaknaan introspektif tentang keindonesian kita tidaklah memadai jika kita mengecualikan zeitgeist (semangat jaman) yang berlaku saat itu, khususnya yang terjadi pada tahun 30-an dan 40-an—dekade-dekade kritis ketika isme-isme besar tengah menggelora dalam konteks Perang Dingin.
Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya. Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat dan fallacy-nya masing-masing. Para intelektual (baca: politikus - EOWI) muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut.
Periode ini, sebagaimana terbukti, sangat menentukan konstelasi politik ekonomi negara-negara di dunia sebagaimana kita kenal dewasa ini. Peperangan antarbangsa dalam skala terbesar termasuk dalam hal korban kemanusiaan mulai berkecamuk, dan tinta sejarah dua kali menamainya sebagai Perang Dunia.
Kurun yang limbung dan berkepanjangan ini tidak hanya dialami oleh negara-negara baru, tapi juga oleh yang telah mapan di benua tua. Ini pula awal kejatuhan dominasi Inggris Raya dan, sebaliknya, awal hegemoni Amerika—tepatnya, awal hegemoni Pemerintah AS terhadap para warga negaranya sendiri dan warga dunia.
Ini juga masa ketika pemerintahan di negara-negara tua tengah mendambakan justifikasi untuk mengatasi kekacauan ekonomi akibat perang yang berkelanjutan.
Pada titik ini, perkembangan ilmu ekonomi sebagai ilmu termuda, pada tahun 30-an ‘berbelok” (atau ‘dibelokkan’) secara curam di sebuah ‘tikungan’ peradaban dan tidak pernah kembali lagi–hingga kini. Ia menjadi (dijadikan) alat justifikasi-kekuasaan paling subtil paling dahsyat hingga ke titik yang belum pernah ada presedennya hingga saat itu.
Dalam pengertian sempit maupun luas, manusia adalah makhluk ekonomi. Dan pemerintahan pada hakikatnya adalah fenomena ekonomi. Berdasarkan ‘pembenaran’ yang kadang diselundupkan dari sains muda ini, terlestarikanlah fungsi setiap pemerintah negara sebagai ‘perencana perekonomian’. Ini satu kenyataan penting terpahit dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ironis, sebab hal tersebut justru berada di luar kepentingan sains yang bebas-nilai ini.
Bahwa kepastian ilmiah dalam ranah sosial lebih sering tidak tercapai, hal ini sepertinya tidak menjadi soal di jaman kita, sebab politik sepertinya lebih mengandalkan pada convenience. Dalam terlalu banyak hal, politik tak lain merupakan perwujudan dari economic violence.
Singkatnya, periode genting tersebut telah mengubah wajah dunia. Sejumlah negara lama mengalami perpecahan, bahkan hilang dari peta bumi. Austro-Hungaria terbelah dua, dan secara signifikan kehilangan pengaruhnya di Eropa. Ceko dan Slavia digabung paksa; Yugoslavia terbentuk (sekarang keduanya terpecah lagi). Sejumlah negara baru bermunculan–termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, India dan lainnya.
Dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan yang meyakinkan: kelirulah kita jika beranggapan bahwa sejarah, termasuk keindonesian kita, berjalan linear, atau bahwa masa lalu adalah perkara yang final.
Pergantian tahun tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan, baik yang besar atau yang kecil. Adalah kenaifan jika kita mengira bahwa harga atas semua kekisruhan yang melahirkan Indonesia sudah terbayar tunai. Berbagai konsekuensinya masih harus dicicil hingga kini.
Pelajaran sejarah lintas-era lintas-negara, baik di negara-negara baru maupun lama, mengonfirmasikan bahwa dominasi negara terhadap individu-individu senantiasa terjadi dan berkulminasi di saat-saat rawan semacam perang. Dominasi pemerintah terhadap individu jauh dari selesai kendati meriam terakhir sudah lama disimpan dan genderang perang tak lagi ditabuhkan. Konsekuensi jangka-panjang yang termahal dari perang adalah berbentuk cengkeraman kuat institusi negara terhadap warganya sendiri.
Inilah bahaya terbesar dan terlanggeng yang sesungguhnya dari setiap peperangan. Ia tak selesai dengan melayangnya ratusan ribu nyawa manusia di ujung bayonet, tetapi terus menjalar hingga mengguritanya omnipotensi matriks pemerintahan hingga mencengkeram aspek-aspek kehidupan pribadi bagi jutaan yang hidup, serta musnahnya peta jalan-pulang ke titik 0 kebebasan.
RENUNGAN
EOWI mencoba menarik beberapa poin dari tulisan sdr. Syahdan, kemudian kita renungkan apakah kita masih perlu pemerintah.
Definisi: pemerintah berarti ’pemberi perintah, komando atau instruksi’. Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya.
Kata sdr Syahdan lagi: dalam kata “pemerintah” terekam jejak yang relatif jelas bagi evolusi sebuah institusi negara, yang (seakan – EOWI) kita jadikan means untuk suatu end.
EOWI menambahkan kata seakan, karena sebenarnya kita – warga negara, rakyat tidak menjadikan negara yang semula sebagai alat (mean) menjadi tujuan (end). Tetapi politikuslah yang menjadikannya dari alat/mean menjadi end/tujuan dengan segala tipu muslihatnya seakan rakyatlah yang menghendakinya.
Ini terlihat dengan penggunaan jargon, propaganda seperti kata sdr Syahdan: Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya. Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat dan fallacy-nya masing-masing. Para intelektual (poitikus – EOWI) muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut.
Rakyat tidak menciptakan jargon dan propaganda, tetapi politikus. Yang mengatakan:
‘Don’t ask what the country can do for you, but ask what can you do for the country.’
Adalah John F Kennedy dengan posisi presiden USA, bukan Kennedy sebagai mayat, atau Kennedy sebagai komandan kapal motor torpedo PT-109 di perang Pasifik.
Apa tujuan akhir dari politikus, seperti kata Syahdan: cengkeraman kuat institusi negara terhadap warganya sendiri. Mencekram, menguasai warganya dan menjadikan budak warganya.
Anda mau bukti? Lihat para TKW di di Airport Sukarno Hatta yang baru pulang dari Timur Tengah. Mereka digiring ke jalur TKW, seperti menggiring ternak. Anda dikenai pajak untuk jasa yang tidak jelas. Jasa apa yang anda terima dari katakanlah departmen tenaga kerja, departemen sosial, departemen agama (selain jasa pelajanan haji, itupun harus bayar dan mahal), departemen pemuda dan olah raga, departemen peranan wanita, wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, DPRD? Padahal setiap tahun kita harus bayar gaji mereka. Tahukah anda bahwa dari 550 anggota DPR, hanya 116 saja yang selalu masuk kerja. Ini sudah termasuk yang tidur selama rapat. Artinya kita hanya perlu maksimum 116 orang untuk bikin undang-undang.
Sebearnya jelas kenapa orang sekarang berondong-bondong mau jadi politikus dan birokrat. Karena dapat uang dan kekuasaan tanpa kerja yang riil. Bentuk lain dari pada keinginan jadi pegawai negri. Absen, tidak pernah masuk tetapi tidak bisa dipecat.
Apakah kita masih perlu pemerintah? Pikirkanlah lagi.
Jakarta 26 Januari 2009.
Sebelum kita memutuskan untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu pemerintah, ada baiknya kita lihat apa arti kata pemerintah. Berikut ini adalah tulisan dari situs sahabat. Tulisannya agak bersifat akademis. Maklum, pengelola situs ini mungkin berkecimpung dibidang akademis atau sejenisnya. Mungkin beliau ini punya gelar PhD, philosophical Doctor.Imam Semar juga punya gelar PhD tetapi artinya – Permanently Head Damage.
ASAL (KATA) PEMERINTAH
Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. I, Edisi 15, Tanggal 30 Desember 2007
Esei singkat di penghujung tahun 2007 ini mengangkat satu pertanyaan: Kapan, di mana dan bagaimana kata ’pemerintah’ muncul pertama kali?
Sejak bertemu Onghokham pertama kali di akhir musim dingin bertahun-tahun lalu hingga beliau wafat, jawaban pertanyaan tersebut masih menggantung; dan hal ini cukup mengecewakan.
(Sebagai sejarawan, Onghokham unik dalam hal ia memfokuskan pusat penelitiannya pada manusia. Setiap kali saya mendapati bukunya di perpustakaan atau di toko buku, sedapat mungkin saya sisihkan waktu untuk mencari jawabannya. Pada ‘ritual’ terakhir, saya cuma menemukan dalam Wahyu Yang Hilang, satu bab yang menarik tentang korupsi yang sejak dulu selalu mendampingi evolusi kekuasaan dan pemerintahan; juga bab tentang pergerakan modal di tangan para pengusaha Cina.)
Maka, maklum, tanpa hasil ‘penggalian’ sejarawan tersebut, artikel ini cuma dapat berhipotesis: bahwa kata ‘Pemerintah’ dipakai pertama kali di masa pra-Indonesia; dia muncul perdana di masa awal bangkitnya semangat kebangsaan, jauh sebelum revolusi fisik menjelang kemerdekaan.
Tentang kapan persisnya, di pamflet atau di koran mana, oleh siapa, dalam aksara apa—Arab gundulkah?—serta untuk mengacu ke pemerintahan yang mana, semuanya masih harus dicari melalui penelitian filologis, sosiologis, atau sejarah yang mendalam.
Sesuai definisinya, pemerintah berarti ’pemberi perintah, komando atau instruksi’. Nuansanya yang militeristik dan/atau paternalistik mencerminkan asimetri antara yang memerintah dan yang diperintah.
Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya. Terminologi ini tentunya cukup cocok untuk mengacu pada hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dan subyek jajahannya. Atau hubungan antara orangtua dan anak—sebelum sang anak beranjak dewasa dan menjadi manusia otonom.
Apakah istilah tersebut pantas diterapkan oleh/pada individu-individu yang konon memiliki kesamaan derajat dan hak? Besar kemungkinan pembaca dapat setuju jawaban ini: tidak.
Jika demikian, apa tidak sebaiknya diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai? Bukankah pada dasarnya, negara adalah kita?
Yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan keberadaan pemerintah itu sendiri. Mempertanyakan muasal kata tersebut hanyalah awal bagi napak tilas yang krusial untuk menelaah secara kritis idiosinkrasi kita dalam memandang fenomena pemerintahan dan konsekuensinya bagi fenomena sehari-hari.
Sama halnya dengan konsep-konsep raya seperti negara, kebangsaan, nasionalisme atau lainnya, konsep pemerintah selalu penting dan relevan ditanyakan dan harus terus dipertanyakan oleh setiap generasi.
Satu klaim yang mendasari introspeksi ini adalah bahwa di dalam kata “pemerintah” terekam jejak yang relatif jelas bagi evolusi sebuah institusi negara, yang kita jadikan means untuk suatu end.
Indonesia modern sebagai sebuah tujuan memang digagas dan dibayangkan oleh segelintir intelektual (baca: politikus- EOWI). Ia diwujudkan bersama dalam berbagai cara, termasuk lewat jalur keras revolusi fisik. Satu hal dapat dipastikan: sebelum negara ini terbentuk, kita sudah ada. (Terlepas dari pandangan Nozick yang cukup menarik tentang negara yang minimalis, tesisnya tentang asal negara berdasarkan sebuah immaculate conception, sangat sulit diterima akal.)
Upaya menuju sebuah Indonesia bermula dari gagasan. Lebih tepatnya, ia lahir dari pertarungan berbagai gagasan yang acapkali berlawanan, meski seringkali tampak saling komplementer.
Lebih lanjut, pemaknaan introspektif tentang keindonesian kita tidaklah memadai jika kita mengecualikan zeitgeist (semangat jaman) yang berlaku saat itu, khususnya yang terjadi pada tahun 30-an dan 40-an—dekade-dekade kritis ketika isme-isme besar tengah menggelora dalam konteks Perang Dingin.
Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya. Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat dan fallacy-nya masing-masing. Para intelektual (baca: politikus - EOWI) muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut.
Periode ini, sebagaimana terbukti, sangat menentukan konstelasi politik ekonomi negara-negara di dunia sebagaimana kita kenal dewasa ini. Peperangan antarbangsa dalam skala terbesar termasuk dalam hal korban kemanusiaan mulai berkecamuk, dan tinta sejarah dua kali menamainya sebagai Perang Dunia.
Kurun yang limbung dan berkepanjangan ini tidak hanya dialami oleh negara-negara baru, tapi juga oleh yang telah mapan di benua tua. Ini pula awal kejatuhan dominasi Inggris Raya dan, sebaliknya, awal hegemoni Amerika—tepatnya, awal hegemoni Pemerintah AS terhadap para warga negaranya sendiri dan warga dunia.
Ini juga masa ketika pemerintahan di negara-negara tua tengah mendambakan justifikasi untuk mengatasi kekacauan ekonomi akibat perang yang berkelanjutan.
Pada titik ini, perkembangan ilmu ekonomi sebagai ilmu termuda, pada tahun 30-an ‘berbelok” (atau ‘dibelokkan’) secara curam di sebuah ‘tikungan’ peradaban dan tidak pernah kembali lagi–hingga kini. Ia menjadi (dijadikan) alat justifikasi-kekuasaan paling subtil paling dahsyat hingga ke titik yang belum pernah ada presedennya hingga saat itu.
Dalam pengertian sempit maupun luas, manusia adalah makhluk ekonomi. Dan pemerintahan pada hakikatnya adalah fenomena ekonomi. Berdasarkan ‘pembenaran’ yang kadang diselundupkan dari sains muda ini, terlestarikanlah fungsi setiap pemerintah negara sebagai ‘perencana perekonomian’. Ini satu kenyataan penting terpahit dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ironis, sebab hal tersebut justru berada di luar kepentingan sains yang bebas-nilai ini.
Bahwa kepastian ilmiah dalam ranah sosial lebih sering tidak tercapai, hal ini sepertinya tidak menjadi soal di jaman kita, sebab politik sepertinya lebih mengandalkan pada convenience. Dalam terlalu banyak hal, politik tak lain merupakan perwujudan dari economic violence.
Singkatnya, periode genting tersebut telah mengubah wajah dunia. Sejumlah negara lama mengalami perpecahan, bahkan hilang dari peta bumi. Austro-Hungaria terbelah dua, dan secara signifikan kehilangan pengaruhnya di Eropa. Ceko dan Slavia digabung paksa; Yugoslavia terbentuk (sekarang keduanya terpecah lagi). Sejumlah negara baru bermunculan–termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, India dan lainnya.
Dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan yang meyakinkan: kelirulah kita jika beranggapan bahwa sejarah, termasuk keindonesian kita, berjalan linear, atau bahwa masa lalu adalah perkara yang final.
Pergantian tahun tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan, baik yang besar atau yang kecil. Adalah kenaifan jika kita mengira bahwa harga atas semua kekisruhan yang melahirkan Indonesia sudah terbayar tunai. Berbagai konsekuensinya masih harus dicicil hingga kini.
Pelajaran sejarah lintas-era lintas-negara, baik di negara-negara baru maupun lama, mengonfirmasikan bahwa dominasi negara terhadap individu-individu senantiasa terjadi dan berkulminasi di saat-saat rawan semacam perang. Dominasi pemerintah terhadap individu jauh dari selesai kendati meriam terakhir sudah lama disimpan dan genderang perang tak lagi ditabuhkan. Konsekuensi jangka-panjang yang termahal dari perang adalah berbentuk cengkeraman kuat institusi negara terhadap warganya sendiri.
Inilah bahaya terbesar dan terlanggeng yang sesungguhnya dari setiap peperangan. Ia tak selesai dengan melayangnya ratusan ribu nyawa manusia di ujung bayonet, tetapi terus menjalar hingga mengguritanya omnipotensi matriks pemerintahan hingga mencengkeram aspek-aspek kehidupan pribadi bagi jutaan yang hidup, serta musnahnya peta jalan-pulang ke titik 0 kebebasan.
RENUNGAN
EOWI mencoba menarik beberapa poin dari tulisan sdr. Syahdan, kemudian kita renungkan apakah kita masih perlu pemerintah.
Definisi: pemerintah berarti ’pemberi perintah, komando atau instruksi’. Istilah ini menegaskan relasi antara majikan dan hamba sahaya.
Kata sdr Syahdan lagi: dalam kata “pemerintah” terekam jejak yang relatif jelas bagi evolusi sebuah institusi negara, yang (seakan – EOWI) kita jadikan means untuk suatu end.
EOWI menambahkan kata seakan, karena sebenarnya kita – warga negara, rakyat tidak menjadikan negara yang semula sebagai alat (mean) menjadi tujuan (end). Tetapi politikuslah yang menjadikannya dari alat/mean menjadi end/tujuan dengan segala tipu muslihatnya seakan rakyatlah yang menghendakinya.
Ini terlihat dengan penggunaan jargon, propaganda seperti kata sdr Syahdan: Pada periode ini jargon-jargon komunisme-sosialisme sedang berada dalam puncaknya. Propaganda demokrasi dan demokratisasi pun sedang mendapatkan momentum terbesarnya. Keduanya sarat dengan daya pikat dan fallacy-nya masing-masing. Para intelektual (poitikus – EOWI) muda Indonesia di dalam dan luar negeri menggagas keindonesian kita dalam kompleksitas tersebut.
Rakyat tidak menciptakan jargon dan propaganda, tetapi politikus. Yang mengatakan:
‘Don’t ask what the country can do for you, but ask what can you do for the country.’
Adalah John F Kennedy dengan posisi presiden USA, bukan Kennedy sebagai mayat, atau Kennedy sebagai komandan kapal motor torpedo PT-109 di perang Pasifik.
Apa tujuan akhir dari politikus, seperti kata Syahdan: cengkeraman kuat institusi negara terhadap warganya sendiri. Mencekram, menguasai warganya dan menjadikan budak warganya.
Anda mau bukti? Lihat para TKW di di Airport Sukarno Hatta yang baru pulang dari Timur Tengah. Mereka digiring ke jalur TKW, seperti menggiring ternak. Anda dikenai pajak untuk jasa yang tidak jelas. Jasa apa yang anda terima dari katakanlah departmen tenaga kerja, departemen sosial, departemen agama (selain jasa pelajanan haji, itupun harus bayar dan mahal), departemen pemuda dan olah raga, departemen peranan wanita, wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, DPRD? Padahal setiap tahun kita harus bayar gaji mereka. Tahukah anda bahwa dari 550 anggota DPR, hanya 116 saja yang selalu masuk kerja. Ini sudah termasuk yang tidur selama rapat. Artinya kita hanya perlu maksimum 116 orang untuk bikin undang-undang.
Sebearnya jelas kenapa orang sekarang berondong-bondong mau jadi politikus dan birokrat. Karena dapat uang dan kekuasaan tanpa kerja yang riil. Bentuk lain dari pada keinginan jadi pegawai negri. Absen, tidak pernah masuk tetapi tidak bisa dipecat.
Apakah kita masih perlu pemerintah? Pikirkanlah lagi.
Jakarta 26 Januari 2009.
Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.


















![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)